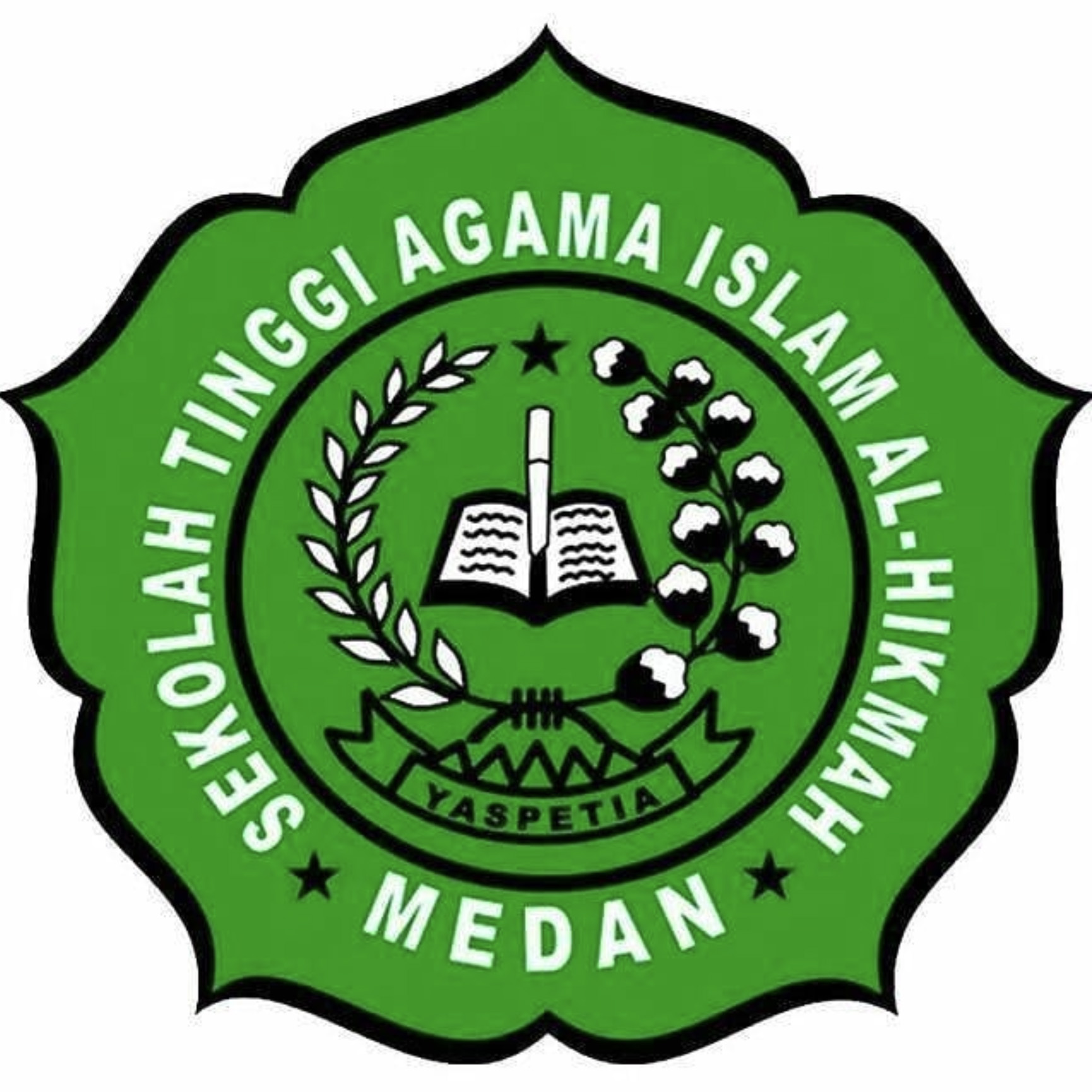Oleh : Dr. Hendra Kurniawan, M.Pd
Jejak kolonial Belanda masih terasa kuat di beberapa wilayah Sumatera Utara, salah satunya di Desa Bulu Cina, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang. Desa ini menyimpan memori panjang tentang masa kejayaan Tembakau Deli yang pertama kali dikembangkan pada abad ke-19. Tembakau dengan kualitas dunia tersebut menjadi primadona ekspor ke Eropa, menjadikan tanah-tanah di Deli sebagai salah satu episentrum perkebunan kolonial. Tak berlebihan bila Kuntowijoyo menyebut sejarah sebagai “rekonstruksi masa lalu untuk kepentingan masa kini dan masa depan”, karena dari jejak inilah kita bisa memahami relasi kolonial yang pernah membentuk wajah desa.
Eksistensi Tembakau Deli membawa dampak besar, bukan hanya pada ekonomi, tetapi juga pada struktur sosial masyarakat. Perkebunan tembakau menghadirkan sistem kerja kontrak yang melibatkan tenaga kerja dari berbagai etnis, termasuk Jawa, Tionghoa, dan India. Akibatnya, Deli menjadi ruang multikultural yang kaya, namun penuh luka kolonial akibat eksploitasi. Di Desa Bulu Cina, sisa-sisa peninggalan perkebunan masih terlihat dari tata ruang dan cerita masyarakat setempat. Ini menegaskan bahwa kolonialisme tidak hanya meninggalkan bangunan fisik, tetapi juga pola relasi sosial dan ekonomi yang membekas hingga kini.
Sampai hari ini, warisan kolonial itu masih berlanjut. Perkebunan yang dahulu dikelola perusahaan Belanda kini menjadi bagian dari PTPN II. Namun, praktik “kuli kontrak” ternyata belum sepenuhnya hilang. Pada musim panen tebu setiap Februari–Maret, perusahaan masih mendatangkan tenaga kerja dari Pulau Jawa untuk bekerja sementara. Hal ini terjadi karena warga setempat, terutama para pemuda, sudah tidak tertarik lagi bekerja di perkebunan. Mereka lebih memilih menjadi kuli bangunan atau bekerja di sektor lain yang dianggap lebih menjanjikan. Situasi ini menunjukkan bagaimana pola kolonial dalam dunia kerja masih bertahan dalam bentuk berbeda.

Meski lahir dari eksploitasi, warisan kolonial itu dalam beberapa hal menjadi modal pembangunan. Irigasi yang dibangun Belanda untuk menunjang perkebunan masih dimanfaatkan masyarakat. Begitu pula sistem pembagian lahan yang awalnya untuk kepentingan korporasi, kini bertransformasi menjadi sumber penghidupan warga desa. Tidak hanya itu, bangunan sumur bor peninggalan Belanda yang menghasilkan air panas dan air higienis masih bisa dijumpai, demikian pula pergudangan tembakau yang menyimpan memori kejayaan ekspor, serta kompleks perumahan zaman Belanda yang hingga kini mempertahankan arsitektur aslinya.
Kini, Desa Bulu Cina tengah mendapat perhatian akademik. Sejumlah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Hikmah Medan melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di desa tersebut. Kehadiran mereka bukan sekadar menjalankan program akademis, tetapi juga menjadi upaya membaca ulang warisan kolonial dengan perspektif baru. Mereka belajar langsung dari masyarakat bagaimana sejarah kolonial membentuk identitas desa, sekaligus menggali potensi lokal yang dapat dikembangkan. Inilah yang oleh Kuntowijoyo disebut “sejarah sebagai ilmu sosial”, yakni menjadikan sejarah relevan untuk aksi sosial dan transformasi.
Dengan demikian, Desa Bulu Cina adalah potret nyata bagaimana jejak kolonial tetap hidup di tengah masyarakat. Tembakau Deli yang dulu menjadi komoditas global kini lebih banyak menjadi kenangan sejarah, namun nilai strategisnya tetap bisa diolah sebagai identitas kultural desa. Mahasiswa, peneliti, dan masyarakat perlu terus menggali, agar warisan kolonial tidak sekadar menjadi nostalgia, tetapi menjadi refleksi kritis untuk membangun masa depan. Sejarah kolonial tidak bisa dihapus, tetapi bisa ditafsir ulang untuk melahirkan peradaban yang lebih adil dan berdaulat.